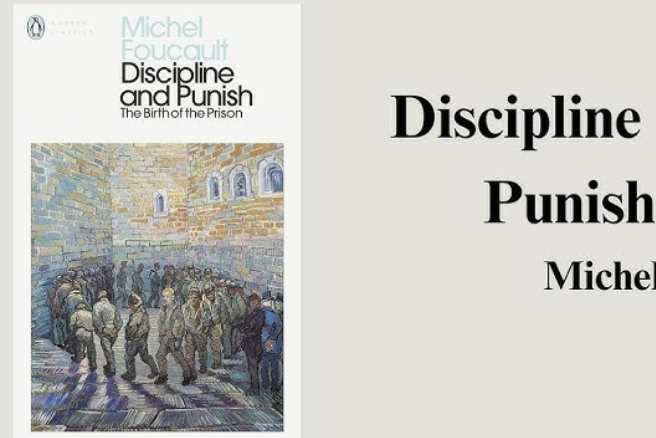Catatan Redaksi:
Dukung kami Hadirkan Tulisan Reflektif di Tengah Derasnya Arus Informasi, dengan Klik Tautan Ini
BICARAA.COM – Ketika Michel Foucault menulis “Discipline and Punish” pada tahun 1975, ia tidak sekadar membedah sejarah penjara, tetapi membuka tabir tentang bagaimana kekuasaan bekerja lewat cara-cara yang tak selalu tampak.
Menurut Foucault, kekuasaan modern tidak lagi menindas secara kasar seperti di masa raja absolut, melainkan mengatur, mengawasi, dan membentuk cara kita berpikir tentang kebenaran.
Dalam konteks Indonesia hari ini, teori Foucault terasa sangat relevan. Kekuasaan tidak hanya hidup di ruang politik, tetapi juga di media, institusi pendidikan, bahkan di media sosial.
Kebenaran tidak lagi datang dari proses berpikir kritis, melainkan dari siapa yang paling sering muncul di layar.
Narasi yang berulang-ulang akhirnya dianggap benar, meski belum tentu memiliki dasar yang kuat.
Media menjadi contoh paling konkret. Dalam lanskap pemberitaan dan opini, siapa yang memiliki akses pada sumber dan jaringan kekuasaan, cenderung lebih mudah membentuk “kebenaran publik”.
Wacana politik dibingkai sedemikian rupa hingga publik lupa bertanya: siapa yang diuntungkan dari semua ini? Foucault menyebut hal semacam ini sebagai regime of truth—sebuah sistem di mana kebenaran tidak bebas, melainkan dikendalikan oleh mereka yang berkuasa.
Kita bisa melihatnya dalam praktik sehari-hari, dari framing isu korupsi yang cepat hilang, sampai kontroversi proyek besar yang diredam lewat narasi “demi pembangunan nasional”.
Di media sosial, kekuasaan hadir dalam bentuk baru: algoritma. Siapa yang menguasai perhatian publik, dialah yang berkuasa. Suara kritis sering dikubur oleh banjir informasi dan propaganda yang lebih menarik secara visual.
Foucault menulis dalam “Power/Knowledge” (1980), bahwa pengetahuan tidak pernah netral — ia selalu merupakan produk relasi kuasa.
Di Indonesia, ini tampak ketika lembaga pendidikan, media, dan bahkan lembaga keagamaan sering kali menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan. Pengetahuan dibentuk untuk menstabilkan sistem, bukan menggugatnya.
Namun, membaca Foucault bukan berarti menolak kekuasaan sepenuhnya.
Justru ia mengajak kita menyadari kekuasaan akan selalu ada yang penting adalah bagaimana mengawasi dan menyeimbanginya.
Dalam masyarakat demokratis, pengawasan balik dari publik (counter-power) menjadi hal yang paling mendesak.
Refleksi Foucault seolah mengingatkan: kebenaran tidak bisa diserahkan pada satu suara tunggal, entah itu pemerintah, media besar, atau algoritma digital.
Kebenaran harus terus diuji melalui percakapan, kritik, dan keberanian berpikir berbeda.
Karena itu, tanggung jawab kita sebagai warga bukan hanya menerima informasi, tetapi menelusuri siapa yang memproduksinya dan untuk tujuan apa.
Seperti kata Foucault, “Di mana ada kekuasaan, di situ selalu ada perlawanan.”
Dan barangkali, di tengah kebisingan informasi hari ini, perlawanan yang paling sederhana adalah berani berpikir sendiri.
Referensi:
Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books, 1977.
Foucault, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. New York: Pantheon Books, 1980.
Eriyanto. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS, 2012.
Aspinall, Edward & Mietzner, Marcus. Indonesia: State and Society in Transition. Singapore: ISEAS, 2019.