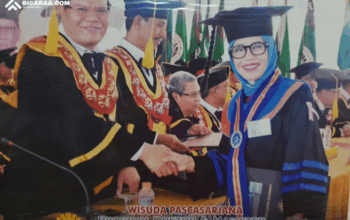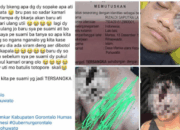Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
Oleh: Dr. Gretty S. Saleh, S.Ip., M.Si.,
Rektor Universitas Pohuwato (UNIPO)
BICARAA.COM– Dalam berbagai literatur klasik maupun modern, kepemimpinan selalu didefinisikan sebagai tanggung jawab moral yang berorientasi pada pelayanan, bukan kekuasaan.
John C. Maxwell dalam bukunya The 21 Irrefutable Laws of Leadership menegaskan inti kepemimpinan bukanlah jabatan, melainkan pengaruh dan keteladanan.
Pengaruh itu akan bertahan lama bila lahir dari keikhlasan, bukan dari kepentingan pribadi.
Konsep kepemimpinan tanpa kepentingan menjadi sangat relevan di tengah era modern yang sering kali menempatkan jabatan sebagai simbol prestise dan alat kekuasaan.
Dalam konteks pendidikan tinggi, kepemimpinan seperti ini bukan hanya penting, tetapi mendesak.
Kampus adalah ruang pembentukan karakter masyarakat, tempat nilai-nilai moral, intelektual, dan sosial ditanamkan.
Oleh karena itu, seorang pemimpin perguruan tinggi dituntut untuk menjadikan pengabdian sebagai panggilan, bukan peluang.
Pemimpin tanpa kepentingan adalah mereka yang tidak menjadikan posisi sebagai sarana memperluas pengaruh atau menguntungkan diri sendiri, tetapi sebagai wadah untuk menebar manfaat dan menjaga martabat institusi.
Ia tidak bekerja untuk mencari pengakuan, melainkan untuk memastikan sistem berjalan dengan adil, transparan, dan berpihak pada kebaikan bersama.
Seperti dikatakan Mahatma Gandhi, “The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.”
Pengabdian kepada orang lain, termasuk kepada mahasiswa dan masyarakat akademik, adalah bentuk tertinggi dari kepemimpinan.
Dalam tradisi kepemimpinan modern, kita mengenal istilah servant leadership, kepemimpinan yang berakar pada pelayanan.
Konsep ini dipopulerkan oleh Robert K. Greenleaf dalam bukunya The Servant as Leader (1970).
Ia menyatakan pemimpin sejati bukanlah mereka yang ingin dilayani, tetapi yang ingin melayani.
Prinsip ini sangat cocok diterapkan di lingkungan kampus, di mana kepemimpinan tidak hanya mengatur, tetapi juga menumbuhkan.
Pemimpin kampus harus menjadi inspirasi moral, yang memberi arah dengan keteladanan, bukan dengan tekanan.
Teladan kepemimpinan tanpa kepentingan juga tampak dari sosok-sosok besar seperti Nelson Mandela dan Ki Hajar Dewantara.
Mandela, meski memiliki kuasa politik besar, tetap menempatkan rekonsiliasi di atas balas dendam.
Sementara Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, menegaskan filosofi kepemimpinan dalam tiga kalimat sederhana.
Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan.
Filosofi ini menjadi dasar moral bagi semua pemimpin pendidikan di Indonesia.
Kepemimpinan tanpa kepentingan juga berarti menjaga jarak dari konflik kepentingan yang sering kali merusak tatanan akademik.
Dunia kampus harus bebas dari praktik-praktik yang menempatkan jabatan sebagai alat politik atau ekonomi.
Kepemimpinan di universitas idealnya dijalankan dengan prinsip meritokrasi, transparansi, dedikasi, serta loyalitas terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
Seorang pemimpin perguruan tinggi tidak hanya memimpin lembaga, tetapi juga memelihara nilai-nilai kebenaran dan kejujuran ilmiah.
Nilai suatu Integritas itu, ketika tetap jujur walaupun tidak ada yang melihat. Tetap benar walaupun tidak ada yang bertepuk tangan untukmu.
Sebab nilai diri diukur bukan dari apa yang kamu lakukan didepan mata orang lain, tetapi konsisten disaat dunia lagi tertidur.
Lebih jauh, kepemimpinan tanpa kepentingan menuntut kepekaan sosial.
Seorang pemimpin kampus tidak boleh hidup di menara gading, terpisah dari realitas masyarakat.
Ia harus hadir sebagai jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat.
Memastikan ilmu pengetahuan benar-benar menjadi solusi atas persoalan sosial dan pembangunan daerah.
Inilah bentuk pengabdian yang sejati ketika ilmu dan kebijakan kampus berdampak langsung pada kehidupan orang banyak.
Pada akhirnya, kepemimpinan tanpa kepentingan adalah tentang keikhlasan dalam mengabdi dan keteguhan dalam menjaga nilai.
Jabatan akan berganti, waktu akan berlalu, tetapi pengaruh dari pemimpin yang tulus akan selalu dikenang.
Seperti Filosofi klasik, dimana Bumi dipijak disitu langit Dijunjung, Filosifi yang mengedepankan Etika, Moral serta Kearifan Lokal
Seperti yang dikatakan Max De Pree juga dalam Leadership Is an Art, “The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant.”
Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin seperti itu di dunia pendidikan pemimpin yang memimpin dengan hati, yang bekerja dengan integritas, dan yang mengabdi tanpa pamrih.
Sebab kepemimpinan sejati bukanlah tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang tetap setia pada kebenaran, bahkan ketika tidak ada yang melihat. (*)