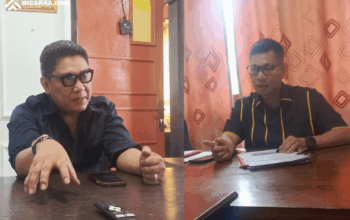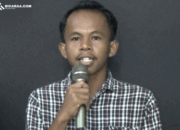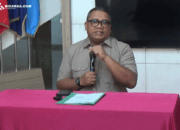Nikmati Update Berita Terbaru dari Bicaraa.com Setiap Hari Melalui Saluran Whatsapp, Bisa Klik Disini
Oleh: Andi Muh. Maulana Asmar
Kader HMI Cabang Pohuwato
GORONTALO, BICARAA.COM– Fenomena Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Pohuwato telah lama menjadi paradoks kebijakan sumber daya alam di Indonesia.
Ia tumbuh di ruang abu-abu antara kebutuhan ekonomi rakyat, absennya regulasi yang berpihak, serta dominasi kepentingan politik-ekonomi lokal.
PETI bukan sekadar praktik ilegal, melainkan cermin dari rekayasa sosial yang dibentuk dan dipelihara oleh struktur kekuasaan.
Dalam perspektif ekonomi politik, PETI Pohuwato menunjukkan bagaimana kekayaan mineral menjadi arena perebutan kuasa.
Pertanyaan klasik Harold Lasswell: “Who gets what, when, and how?” menemukan relevansinya di sini.
-Elit politik sering memanfaatkan isu PETI sebagai alat legitimasi menjadi patron bagi penambang rakyat demi modal sosial elektoral.
-Korporasi besar melihatnya sebagai kompetitor liar, tetapi ironisnya sering menggunakan narasi PETI untuk menekan pemerintah agar memberi konsesi yang lebih luas.
-Masyarakat lokal, yang seharusnya pemilik sah sumber daya, justru terjebak menjadi buruh tambang berisiko tinggi tanpa kepastian perlindungan hukum dan lingkungan.
Dengan logika itu, PETI adalah rekayasa sosial yang mempertahankan status quo: rakyat tetap bergantung, elit tetap berkuasa, dan lingkungan tetap dikorbankan.
Dilema Negara dan Ambiguitas Kebijakan
Pemerintah daerah berada dalam pusaran dilema. Menutup PETI berarti mencabut sumber nafkah ribuan warga yang hidup dari tambang emas.
Membiarkannya beroperasi berarti merawat praktik ilegal yang merusak lingkungan dan memperlebar lubang hitam hukum.
Ambiguitas ini bukanlah kelemahan semata, melainkan bagian dari desain rekayasa sosial: negara hadir setengah hati, justru agar PETI bisa dijadikan “alat kendali sosial-politik.”
Legalitas tambang rakyat dengan skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kerap dijadikan solusi formal.
Namun dalam praktiknya, WPR hanya menjadi kosmetik kebijakan.
Izin memang keluar, tetapi akses alat, modal, dan pasar tetap dikuasai pemodal besar, bukan penambang lokal.
Alhasil, PETI tetap tumbuh di bawah bayang-bayang kapital ekstraktif.
Salah satu bentuk rekayasa sosial paling halus adalah penciptaan narasi bahwa PETI adalah “urat nadi ekonomi rakyat.”
Narasi ini dikapitalisasi untuk menjustifikasi keberadaan tambang ilegal sekaligus meredam kritik terhadap kerusakan lingkungan.
Padahal, jika ditelusuri, keuntungan paling besar justru tidak dinikmati rakyat kecil, melainkan para pemodal, pengepul, hingga aktor politik yang bermain di balik layar.
Rakyat hanya menjadi perisai moral: ketika aparat turun menertibkan, yang ditampilkan adalah wajah rakyat miskin yang kehilangan penghidupan.
Bukan jaringan elite yang mengatur distribusi alat berat, bahan kimia, dan pasar emas. Inilah bentuk ketidakadilan struktural yang dibungkus dalam narasi kerakyatan.
Kerusakan yang Diwariskan
PETI Pohuwato tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga meninggalkan jejak ekologis yang panjang: hutan gundul, sungai tercemar merkuri, dan tanah yang kehilangan daya hidup.
Ironisnya, kerusakan ini akan diwariskan kepada generasi yang justru tidak pernah menikmati emasnya. Inilah tragedi klasik ekonomi ekstraktif: keuntungan privat dinikmati segelintir orang, sementara kerugian ekologis dan sosial menjadi beban kolektif.
Pertanyaan mendasar bagi ekonomi politik daerah adalah: apakah negara akan terus membiarkan rekayasa sosial ini berlangsung? Ataukah akan berani membongkar jaringan kepentingan yang melanggengkannya?
Solusi tidak bisa berhenti pada formalitas legalisasi. Diperlukan:
Reformasi tata kelola: transparansi dalam pemberian izin, pengawasan distribusi alat berat dan bahan kimia, serta penindakan terhadap aktor besar, bukan hanya penambang kecil.
Keadilan distributif: memastikan rakyat Pohuwato benar-benar mendapat akses legal, teknologi ramah lingkungan, dan kepastian pasar.
Restorasi ekologis: setiap kebijakan tambang harus mengandung rencana pemulihan lingkungan, bukan sekadar kalkulasi keuntungan jangka pendek.
Penutup: Politik Keberpihakan
Masalah PETI Pohuwato pada akhirnya bukan sekadar soal hukum atau ekonomi, melainkan soal keberpihakan politik. Apakah pemerintah daerah berani berpihak pada rakyat dan lingkungan, atau terus tunduk pada logika kapital ekstraktif yang merusak?
Selama jawaban atas pertanyaan itu masih kabur, PETI Pohuwato akan tetap menjadi laboratorium rekayasa sosial: rakyat dibiarkan hidup dalam ketidakpastian, elit menuai legitimasi, dan bumi Pohuwato terus dieksploitasi tanpa ampun. (*)